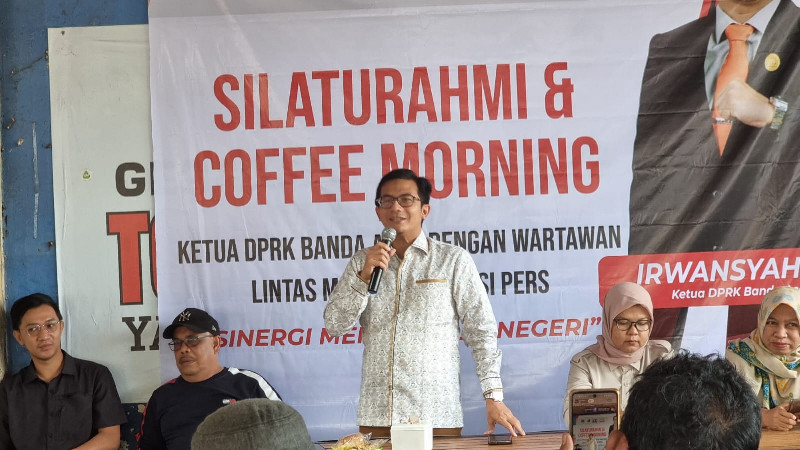Qanun KKR “Taring Pusat” Mencengkram Aceh
Font: Ukuran: - +
Reporter : Bahtiar Gayo

DIALEKSIS.COM| Indept- Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan wewenang untuk Aceh dalam menentukan arah kebijakan, khususnya kepada mereka korban konflik. Pemerintah pusat bagaikan melepas kepala, namun ekor tetap dicengkram.
Aceh kini dibuat “gaduh” ketika pemerintah pusat meminta Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Pemerintah pusat mempersoalkan keabsahan hukum pembentukan KKR dalam konteks undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Apakah Aceh diam dengan permintaan Pemerintah Pusat? Tidak! Perlawanan diberikan. Beragam pihak menyoroti tajam surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Apa pertimbangan pemerintah pusat untuk mencabut KKR Aceh. Bagaimana reaksi rakyat Aceh? Haruskah Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 terkait KKR dihapus, dengan merujuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional yang dibatalkan pada 2006 oleh Mahkamah konstitusi. Dialeksis.com merangkum dalam sebuah catatan khsusus.
Sikap Pemerintah Pusat
Reaksi pemerintah pusat muncul sehubungan dengan adanya draf qanun yang sedang digodok DPRA, tentang perubahan terhadap Qanun KKR Aceh. Qanun ini nantinya akan semakin memperkuat kelembagaan KKR Aceh, agar dapat bekerja lebih optimal dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
Pemerintah Aceh pada September 2024 ahirnya mengirimkan surat ke Kemendagri, memohon fasilitasi sehubungan dengan adanya rancangan perubahan Qanun KKR Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Reaksi pemerintah pusat ternyata mengejutkan.
Surat Kemendagri yang ditujukan ke Pj Gubernur Aceh, pada 7 November 2024 secara resmi menanggapi rancangan qanun atas perubahan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.
Dalam suratnya Kemendagri menjelaskan, bahwa rancangan qanun tersebut telah dikaji secara mendalam dari sisi formal dan materiil. Kajian ini menyoroti beberapa poin penting, terutama mengenai keabsahan hukum pembentukan KKR dalam konteks undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Hal ini mengindikasikan bahwa KKR di Aceh tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengikuti regulasi nasional yang mengatur keberadaan KKR pada tingkat yang lebih luas.
Kementerian Dalam Negeri merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang seharusnya menjadi dasar hukum pembentukan KKR.
Undang-undang ini telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tujuan KKR, yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum (rechtszekerheid).
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan kajian tersebut, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyarankan kepada Pemerintah Aceh untuk mempertimbangkan pencabutan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 terkait KKR.
Pemerintah Aceh diharapkan untuk menyusun ulang kebijakan rekonsiliasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Tindakan ini diharapkan agar pelaksanaan rekonsiliasi di Aceh dapat berjalan dengan efektif dan berlandaskan hukum yang lebih kuat.
Surat Kemendagri ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu untuk memastikan bahwa kebijakan rekonsiliasi yang dijalankan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.
Sikap Pemerintah Aceh
Mendapat balasan surat dari pemerintah pusat yang mengejutkan dan menusuk relung hati rakyat Aceh, Pemerintah Aceh menyebutkan, pihaknya akan melakukan kajian yang mendalam dan tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan.
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Junaidi, SH, MH, menyebutkan, Pemerintah Aceh akan melakukan kajian mendalam. Pemerintah Aceh menghargai rekomendasi Kemendagri, namun pihaknya juga mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus.
“Kami akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap saran tersebut dengan mengacu pada prinsip keistimewaan Aceh. Pemerintah Aceh sangat memahami bahwa keberadaan KKR merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi dan pencarian kebenaran yang signifikan, terutama untuk menyelesaikan konflik masa lalu di Aceh,” ujar Junaidi dalam keteranganya kepada media.
Junaidi menjelaskan, bahwa Pemerintah Aceh tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berimplikasi besar terhadap keberlanjutan program-program rekonsiliasi yang telah berjalan.
“Lembaga KKR Aceh memiliki peran yang penting sebagai sarana untuk memberikan ruang bagi masyarakat Aceh yang terdampak konflik masa lalu, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan perdamaian,” jelasnya.
Selama ini, kata Junaidi, KKR Aceh sudah memberikan kontribusi dalam membuka ruang bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka serta memperjuangkan hak-hak mereka.
“Kita perlu berhati-hati agar keputusan yang diambil nanti tetap mempertimbangkan kebermanfaatan dan kesesuaian dengan aspirasi masyarakat Aceh,” jelas Junaidi.
Pemerintah Aceh menyadari bahwa terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional. Namun, pihaknya juga menekankan bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus yang diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Oleh karena itu, jelas Junaidi, Pemerintah Aceh akan memperhitungkan setiap aspek agar keputusan terkait KKR tidak mengabaikan prinsip-prinsip otonomi khusus yang dijamin undang-undang.
“Kami perlu memastikan bahwa apapun keputusan yang diambil tetap selaras dengan hak keistimewaan Aceh. Tidak hanya dalam aspek formal, tetapi juga dalam nilai-nilai rekonsiliasi yang selama ini menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh,” tegas Junaidi.
Impunitas
Sikap pemerintah pusat dalam mengutak-atik KKR Aceh memunculkan reaksi berbagai pihak, terutama kalangan aktivis di Aceh. Menghilangkan KKR di Aceh adalah bentuk impunitas, menghilangkan hukuman terhadap apa yang terjadi di Aceh.
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, dia menilai baru dua puluh hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, sejumlah langkah kontroversial terkait impunitas muncul dan menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan, khususnya di Aceh.
Menurut Azharul Husna dalam keterenganya kepada Dialeksis.com, rekomendasi dari Kemendagri, melalui Ditjen Otda yang menyarankan agar Pemerintah Aceh mencabut Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh adalah salah satu bentuk impunitas.
Rekomendasi ini sebagai upaya yang dapat menghambat proses pengungkapan kebenaran terkait pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik di Aceh. Azharul Husna, menilai langkah tersebut adalah bagian dari upaya sistematis untuk melanggengkan impunitas.
"Baru dua puluh hari rezim Prabowo berjalan, namun sudah ada indikasi kuat untuk menutup ruang keadilan dan kebenaran bagi korban pelanggaran HAM di Aceh,” jelasnya.
Hal itu dimulai dari wacana pencabutan status Soeharto sebagai pelaku pelanggaran HAM hingga upaya memaksa penutupan kasus Munir, kini giliran KKR Aceh yang ingin 'diselesaikan' dengan cara yang bertentangan dengan semangat perdamaian," ujar Azharul.
Menurut Azharul, hal ini jelas merupakan upaya untuk menghapus sejarah dan menutup hak korban atas kebenaran dan pemulihan yang merupakan hak asasi mereka. Menurutnya, KKR Aceh tidak bergantung pada UU KKR Nasional.
"KKR Aceh lahir dari semangat perdamaian yang dituangkan dalam MoU Helsinki dan didukung oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini adalah komitmen suci untuk menghormati hak korban," tegasnya.
KKR Aceh dibentuk sebagai salah satu mekanisme keadilan transisi yang diberlakukan pasca-perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada tahun 2005.
Fungsi KKR Aceh tidak hanya mencakup rekonsiliasi, tetapi juga pengungkapan kebenaran serta rekomendasi bagi reparasi kepada korban, jelasnya.
“Menghapus KKR Aceh berarti memutus mekanisme penting untuk mengungkapkan pelanggaran HAM di masa lalu. KKR Aceh bukan sekadar sarana rekonsiliasi. Ini adalah amanah dari MoU Helsinki yang membawa martabat dan hak korban dalam mencari kebenaran dan mendapatkan pemulihan,” sebutnya.
Jika KKR Aceh dicabut, ini sama saja dengan menutup pintu bagi kebenaran, memutus sejarah, dan menghalangi hak korban atas keadilan. Jika dasar hukum KKR Aceh adalah KKR Nasional yang telah dicabut, maka KKR Aceh seharusnya tidak pernah berdiri sejak awal, sebutnya.
"Faktanya, Qanun KKR Aceh disahkan pada tahun 2013, jauh setelah KKR Nasional dicabut pada tahun 2007. Ini menunjukkan bahwa KKR Aceh memiliki legitimasi tersendiri dan tidak terikat dengan KKR Nasional," katanya.
Menurut Azharul, surat Kemendagri ini seakan menunjukkan sikap Pemerintah Pusat yang tidak menghargai peran KKR Aceh dalam menjaga perdamaian. KKR Aceh adalah anak kandung perdamaian Aceh. Usaha untuk menutup atau mencabut KKR Aceh sama dengan melukai kembali korban yang selama ini menanti keadilan," ungkapnya.
Dia mendesak Pemerintah Aceh agar menolak saran dari Dirjen Otda. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh harus bersikap tegas dan tidak boleh membiarkan ini terjadi.
Pemerintah Aceh harus menjawab surat ini dengan jelas, bahwa KKR Aceh adalah amanah dari perdamaian yang telah susah payah dicapai. Hak korban tidak boleh diabaikan hanya karena regulasi formal yang tak relevan," ujarnya.
Azharul juga mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran adalah hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berhak mengetahui apa yang terjadi dan berhak mendapatkan pemulihan.
“Setiap upaya untuk menutup KKR Aceh berarti menolak hak-hak ini. Kami tidak akan tinggal diam jika hak korban diinjak-injak,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia Harus Belajar dari KKR Aceh
Soal rencana pencabutan KKR Aceh yang direkomendasikan Kemendagri juga mendapat tanggapan keras dari Aulianda Wafisa, Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Banda Aceh. Dia menyayangkan langkah Kemendagri mereduksi makna perdamaian dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.
“KKR Aceh adalah anak kandung dari kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam MoU Helsinki 2005,” tegas Aulianda kepada Dialeksis.com, Selasa, 12 November 2024.
Aulianda menjelaskan bahwa semangat pendirian KKR Aceh berbeda dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional yang dibatalkan pada 2006. Pembentukan KKR Aceh bukan bergantung pada KKR Nasional, melainkan pada kesepakatan perdamaian.
“MoU Helsinki mengamanatkan sebuah komisi khusus yang berfokus pada pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh. Dengan kata lain, keberadaan KKR Aceh berdiri sendiri berdasarkan kebutuhan khusus Aceh,” jelas Aulianda.
Menurut Aulianda, Qanun KKR Aceh tidak dapat begitu saja dibatalkan hanya karena KKR Nasional sudah tidak ada. Jika KKR Aceh bergantung pada KKR Nasional, seharusnya ia tak pernah ada sejak awal. Kenyataannya, KKR Aceh justru lahir dari semangat yang berbeda dan memiliki dasar hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA),” tambahnya.
Aulianda juga menekankan bahwa KKR Aceh mendapat perhatian dan pujian internasional sebagai contoh penyelesaian konflik berbasis keadilan dan pemulihan korban. Banyak negara, seperti Timor Leste, Filipina, dan Myanmar, mengirim perwakilan untuk mempelajari model KKR Aceh dalam upaya meredam konflik di negara mereka.
“Pemerintah Indonesia diakui dunia internasional berkat KKR Aceh. Ini menunjukkan bahwa keberadaan KKR Aceh bukan hanya berarti bagi rakyat Aceh tetapi juga menjadi contoh positif bagi rakyat Indonesia,” ungkap Aulianda.
Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya justru menjadikan KKR Aceh sebagai acuan untuk mendirikan kembali KKR Nasional, bukan malah mempersoalkan keberadaannya.Keberadaan KKR Aceh harus dilihat sebagai langkah yang sesuai dengan semangat perdamaian dan penghormatan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM.
“KKR Aceh adalah lembaga satu-satunya yang berpusat pada kepentingan korban. Ini adalah lembaga khusus yang memiliki tujuan utama mengakui kebenaran, memberikan reparasi, dan memulihkan martabat korban. Langkah-langkah untuk menghapus KKR Aceh sama saja dengan mengabaikan hak-hak mereka,” ujarnya.
Menurut Aulianda, tanggapan Kemendagri menunjukkan bahwa perdebatan ini masih berkutat pada pandangan formalistik semata tanpa memperhatikan makna substantif yang terkandung dalam KKR Aceh.
"Menghapus KKR Aceh dengan hanya berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus KKR Nasional, menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami konteks spesifik Aceh. Seharusnya pemerintah pusat membaca situasi Aceh dengan kacamata yang lebih luas, melihat perdamaian dan hak-hak korban sebagai hal yang utama,”pinta Aulianda.
Dalam pandangan YLBH Banda Aceh, KKR Aceh merupakan komponen integral dari perdamaian yang telah diraih Aceh melalui upaya panjang dan berliku. Pembatalan Qanun KKR Aceh bukan hanya akan menjadi sebuah kemunduran bagi Aceh, tetapi juga akan mencederai martabat perdamaian yang selama ini telah dicapai.
“Kami mendesak Pemerintah Aceh untuk menolak saran pencabutan ini dan mempertahankan KKR Aceh demi menghormati hak-hak korban,” tegas Aulianda.
Ke depan, YLBH Banda Aceh berharap pemerintah pusat dan Kemendagri dapat lebih bijaksana dalam mengambil langkah terkait isu-isu sensitif yang berhubungan dengan perdamaian di Aceh.
“KKR Aceh adalah simbol perdamaian dan pengakuan atas hak korban. Setiap upaya untuk menghapus keberadaan KKR Aceh adalah bentuk pengkhianatan terhadap perdamaian itu sendiri,” tutup Aulianda.
KKR Aceh Tidak Akan Berubah
Menanggapi upaya pemerintah pusat untuk menghapus KKR di Aceh, pihak KKR Aceh menyatakan tekadnya tidak akan berubahah dan tetap komitmen dalam menjalankan mandat rekonsiliasi dan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.
Menurut ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, pihaknya telah bekerja dan akan terus bekerja sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh.
"Qanun ini merupakan hasil kerja keras masyarakat Aceh yang menginginkan pemulihan dari trauma masa lalu, dan kami merasa bahwa kehadiran KKR Aceh sudah menjadi bagian penting dari proses itu,” ungkap Masthur kepada Dialeksis.com, Selasa, 12 November 2024.
KKR Aceh pertama kali terbentuk pada tahun 2016, setelah pemilihan komisioner yang dilakukan oleh DPRA. Sejak itu, KKR Aceh terus melakukan upaya pengumpulan pernyataan dari para korban pelanggaran HAM di masa konflik.
Hingga saat ini, lebih dari 6.000 korban dari 14 kabupaten/kota di Aceh telah memberikan kesaksian dan berbagi pengalaman mereka dalam upaya pengungkapan kebenaran.
Menurut Masthur, data-data yang dikumpulkan oleh KKR Aceh , menjadi landasan bagi rekomendasi reparasi dan pemulihan korban, serta program rekonsiliasi yang diusulkan kepada pemerintah pusat.
KKR Aceh juga beberapa kali mengadakan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, serta Kantor Staf Presiden untuk menyampaikan rekomendasi pemulihan bagi para korban.
“Tidak hanya itu, kami juga diundang untuk memberikan masukan dalam Penyelesaian Non Yudisial terkait tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh, yakni peristiwa Simpang KKA, Jambo Keupok, dan Rumoh Geudong yang ditangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2023. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengakui peran penting KKR Aceh,” ujar Masthur.
Masthur menegaskan bahwa Qanun KKR Aceh adalah produk hukum yang dibuat berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Qanun KKR Aceh lahir dari semangat otonomi daerah dan perdamaian yang telah kita capai. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghormati dan mengakui hak-hak korban pelanggaran HAM di Aceh,” ujar Masthur.
Menurutnya, KKR Aceh akan terus melanjutkan upayanya untuk mendukung para korban dengan program reparasi dan pendekatan rekonsiliasi.
Tahun ini, DPRA bahkan sedang menginisiasi perubahan terhadap Qanun KKR Aceh guna memperkuat kelembagaan KKR Aceh agar dapat bekerja lebih optimal dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
Dalam kerangka kerjanya, KKR Aceh telah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Termasuk dalam mempersiapkan mekanisme pelaksanaan reparasi dan penyempurnaan konsep memorialisasi yang berbasis kearifan lokal.
“Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai,” tutur Masthur.
KKR Aceh juga berencana memperkuat upaya rekonsiliasi bagi korban yang membutuhkan, termasuk mengadakan berbagai program yang mendukung pemulihan psikologis dan sosial bagi mereka.
"Rekonsiliasi adalah proses panjang yang memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, dan kami siap melanjutkannya selama masih ada dukungan dari masyarakat Aceh,” tegas Masthur.
Pihaknya berharap agar pemerintah pusat dapat memahami bahwa keberadaan KKR Aceh adalah bagian penting dari upaya Aceh dalam mempertahankan perdamaian dan keadilan.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa lebih memahami konteks historis dan hukum di Aceh serta mendukung upaya kami untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai,” jelas Masthur.
Pemerintah Pusat sudah mengusik ketenangan masyarakat Aceh, ingin mencabut KKR di negeri ujung barat Pulau Sumatera ini. Surat Kemendagri telah memunculkan reaksi. Apakah KKR di Aceh akan hilang dan hanya menjadi kenangan dalam catatan sejarah?
Rakyat Aceh memberikan perlawanan, KKR Aceh harus tetap ada di bumi Serambi Mekkah ini. Bagaimana kelanjutan dari upaya pemerintah untuk menghapus KKR di Aceh. Waktu terus bergulir, reaksi bermunculan, bagaimana kisah ahirnya? *** Bahtiar Gayo.
- Tanggapi Saran Kemendagri, KKR Aceh: Komitmen Kami Melaksanakan Mandat dan Tugas Tidak Berubah
- LBH Banda Aceh: Pemerintah Indonesia Harus Belajar dari KKR Aceh, Bukan Hapus Qanun
- Langkah Pusat Terhadap KKR Aceh Dinilai Cederai Perdamaian, KontraS: Jangan Abaikan Hak Korban
- KKR Aceh Dorong Program Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Masuk Rencana Pembangunan Nasional
Berita Populer
.jpg)






 Sebelumnya
Sebelumnya